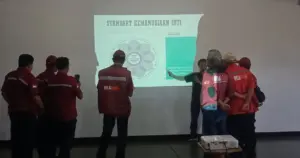Bantul Minggu (26/10), GEMA doa dan nyanyian umat bergema di Gereja St. Theresia Sedayu. Pagi itu, ada yang lebih terasa dari sekadar suara. Yakni semangat keterbukaan: semua umat, termasuk penyandang disabilitas, diterima untuk beribadat dan terlibat secara penuh dalam kehidupan menggereja.
Menurut Romo Antonius Koko Kristanto, semangat inklusivitas berakar dari pandangan Gereja bahwa setiap orang diciptakan seturut citra Allah. “Semua umat, termasuk difabel, memiliki martabat dan panggilan yang sama untuk bergotong royong membangun Gereja,” ujarnya. Bagi Gereja St. Theresia, inklusivitas berarti keterbukaan tanpa membeda-bedakan. “Kita semua bagian dari satu tubuh Kristus,” tambah Romo Koko.
Namun, perjalanan menuju Gereja sebagai tempat ibadah yang ramah disabilitas tidak selalu mudah. Romo Koko mengakui bahwa sebagian umat masih memahami difabel dipandang sebagai objek belas kasihan, bukan subjek iman . “Padahal mereka memiliki different ability. Mereka bukan orang yang perlu dikasihani,” tegasnya. Mengakui kesetaraan martabat, memberikan kepercayaan penuh serta mengakui bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.

Secara fasilitas, Gereja St. Theresia Sedayu telah berupaya memenuhi aksesibilitas, meski belum sepenuhnya sempurna. Tantangan masih ada, seperti kebutuhan bahasa isyarat saat misa dan akses menuju altar. Karena itu, Gereja terus mendorong keterlibatan keluarga dan relawan untuk menjadi jembatan komunikasi dan memastikan seluruh umat dapat memahami pesan iman dengan utuh.
Langkah konkret lain tampak melalui Misa Inklusi. Misa bersama seluruh umat, yang digelar setiap tahun sebagai ruang refleksi dan perjumpaan. “Misa ini bukan sekadar seremoni, tapi menjadi cara Gereja menyadarkan umat bahwa difabel adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama,” tutur Romo Koko.
Sarasehan Gereja Ramah Disabilitas yang diselenggarakan di Kevikepan Yogyakarta Barat menjadi bagian penting dari gerak pastoral itu. Menurut Ketua Panitia Kegiatan Maria Tri Suhartini, sarasehan ini lahir dari kerinduan para difabel dan keluarga mereka untuk saling bertemu dan berbagi pengalaman iman. “Difabel bisa mengakses tempat ibadah, itu hak semua. Gereja berupaya memberikan aksesibilitas dan advokasi agar setiap umat dapat beribadat dengan damai,” ujarnya. Tahun ini, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Paroki (HARPA) 2025, memperingati 98 tahun Gereja St. Theresia Sedayu.
Pada kesempatan itu salah satu peserta difabel Andreas Sardjianto, ia merasakan kehangatan penerimaan tersebut. “Saya merasa diterima dan dilibatkan,” katanya. Ia berharap ke depan gereja-gereja lain pun meniru langkah St. Theresia Sedayu. Sehingga difabel tidak hanya hadir sebagai penerima perhatian, tetapi juga pelayan dan penggerak iman. “Mungkin suatu hari nanti, akan ada koor yang seluruhnya difabel,” harapnya.

Melalui paparannya pada sarasehan, pemerhati isu disabilitas Angga Yanuar, menekankan pentingnya menghapus stigma dan sikap ableisme dalam lingkungan iman. Ia mengingatkan bahwa memisahkan manusia dari pengambilan keputusannya sendiri berarti menjadikannya objek, bukan subjek. Gereja yang inklusif adalah gereja yang berani memberi ruang bagi setiap umat untuk menentukan arah hidup dan imannya sendiri.
Romo Koko menutup dengan pesan pastoral yang hangat: “Kita semua adalah satu tubuh. Tidak semua memiliki kesamaan, tetapi masing-masing memiliki keunikan dan kemampuan berbeda. Mari membuka hati dan memberi ruang bagi semua saudara-saudari tanpa membeda-bedakan—untuk berkarya, beriman, dan bersaksi bersama.” [harta nining wijaya]